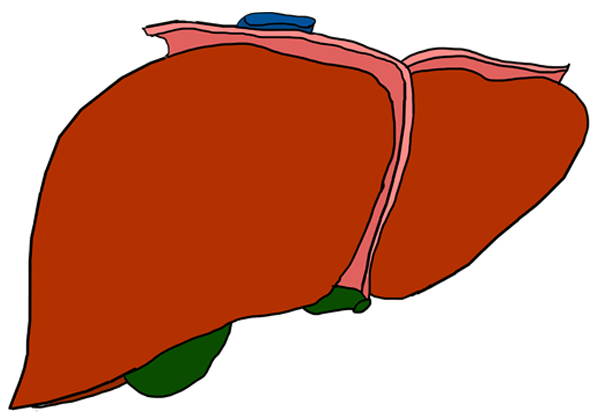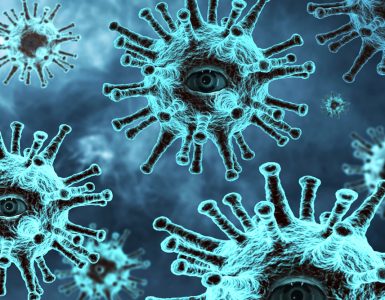Pasien cuci darah berisiko tertular hepatitis C. Pada kasus seperti ini, tatalaksananya berbeda.
Angka hepatitis C pada pasien gagal ginjal yang menjalani hemodialisis (HD), sangat tinggi. Di dunia, angkanya berkisar antara 3-68%. Di Indonesia, datanya bervariasi. Misalnya di RS Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta, pada 1997 mencapai 72%. “Data terakhir 2011 itu 38%, dan sekarang sedang dilakukan penelitian,” ungkap Ketua Peneliti Hati Indonesia (PPHI) dr. Irsan Hasan, Sp.PD-KGEH. Di RSUP Dr. Sardjito, Yogyakarta, ditemukan 55%; di Surabaya 76,3% dan 88%. Adapun menurut Hasil Surveilans Ditjen P2PL 2007-2012, besarannya secara nasional mencapai 15,16%.
Banyak kemungkinan mengapa penularan hepatitis C melalui HD demikian tinggi. SOP (standar operasional prosedur)-nya menuntut penggunaan alat harus steril. Jarum misalnya, hanya sekali pakai lalu diganti dengan yang baru untuk pasien berikutnya. “Mungkin perlu dikaji, apakah SOP dijalankan atau tidak,” ujar dr. Wiendra Woworuntu, M.Kes, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Ditjen P2PL Kemenkes RI.
Sebagai sub spesialis KGEH, dr. Irsan mendiskusikan masalah tingginya penularan hepatitis C pada pasien cuci darah, dengan sejawatnya di bidang ginjal. Menurutnya, petugas medis sudah menjalankan HD sesuai dengan SOP. Namun memang ada beberapa hal yang perlu dikaji lebih jauh.
Dulu, alat filter untuk HD dibersihkan, lalu dipakai ulang untuk pasien yang sama (reuse dialyzer). Ini juga dilakukan di banyak negara lain. “Namun dipertanyakan apakah hal ini aman, sehingga tidak dilakukan lagi,” ujar dr. Irsan. Turunnya angka hepatitis C di RSCM dari 72% (1997) menjadi 38% (2011), bisa jadi karena reuse dialyzer tidak lagi dikerjakan.
Ada dugaan, penularan tidak langsung dari HD. Misalnya melalui transfusi darah, mengingat pasien gagal ginjal kronik biasanya memiliki kadar Hb rendah hingga mengalami anemia dan memerlukan transfusi. Namun ada juga pasien yang tetap kena hepatitis C meski tidak pernah transfusi dan filter dialisernya sekali pakai.
Beberapa hal lain yang dicurigai misalnya penggunaan heparin, obat pengencer darah yang disuntikkan. Satu vial heparin dipakai untuk beberapa orang. Bisa jadi, tanpa sengaja ini menjadi jalur penularan hepatitis C. Atau, mungkin saja dari sarung tangan perawat. “Untuk perawatnya aman. Tapi bisa jadi habis menangani seorang pasien dengan berdarah, lalu menangani pasien lain yang juga berdarah,” tutur dr. Irsan.
Sebaliknya, hepatitis juga bisa menimbulkan gangguan pada ginjal, berupa peradangan sel-sel ginjal (glomerulonefritis). “Namun, ini tidak serta merta menjadi gagal ginjal kronis yang harus cuci darah. Jauh lebih banyak yang hemodialisis lalu kena hepatitis C,” terang dr. Irsan.
Tatalaksana berbeda
Pada masa interferon, pengobatan hepatitis C pada pasien gagal ginjal yang sudah menjalani HD bisa dibilang seperti buah simalakama, karena efek sampingnya berat. Akhirnya dibuat protokol, pasien gagal ginjal yang akan menjalani transplantasi (cangkok) ginjal, harus diterapi interferon dulu. Namun ini bukan hal mudah. Kondisi pasien bisa drop bahkan meninggal, saat menjalani terapi interferon.
Dibuat aturan baru. Pasien yang akan cangkok ginjal tapi memiliki virus hepatitis C, dilihat dulu seberapa berat kondisi levernya. Kalau masih baik meski ada virus, ia menjalani cangkok tanpa terapi interferon. Namun bila kondisi hatinya sudah jelek, cangkok ginjal dibatalkan, karena obat penekan sistem imun (imunosupresan) yang harus diminum seumur hidup setelah transplantasi, bisa memperburuk kondisi lever. “Aturannya, dicangkok ginjal dan hatinya,” jelas dr. Irsan. Namun transplantasi lever sangat mahal (sekitar Rp 4 miliar); tidak banyak pasien yang sanggup membayar transplnatasi lever dan ginjal sekaligus.
Kita bersyukur, pengobatan hepatitis C kini masuk ke era DAA. Dulu sebelum ada DAA, pasien HD dengan hepatitis C seperti menemui jalan buntu. Dengan DAA, pasien HD bisa mendapat pengobatan yang mumpuni untuk hepatitis C-nya. Ada pertanyaan yang mengemuka: apakah tidak percuma bila hepatitis C diobati, karena pasien terus menjalani HD; bisa saja ia kembali tertular virus tersebut. Bagaimanapun, mendapat pengobatan adalah hak asasi pasien; mereka tetap berhak mendapat obat yang terbaik.
Ada rencana protokol, pasien gagal ginjal yang hendak menjalani tranplantasi ginjal, diobati dulu hepatitis C-nya dengan DAA. “Ada catatan. Sofosbuvir tidak dianjurkan pada pasien yang filtrasi ginjalnya kurang dari 30,” imbuhnya. Di balik segala keistimewaannya, sofosbuvir tidak bisa diberikan pada pasien yang fungsi ginjalnya jelek, karena dibuang lewat ginjal. “Kalau ginjalnya tidak bisa bekerja, obat akan menumpuk di dalam tubuh,” imbuhnya.
Kembali terjadi perdebatan. Sebagian ahli berpendapat bahwa sofosbuvir bisa diberikan pada pasien yang menjalani HD, karena toh fungsi ginjalnya sudah digantikan dengan mesin, jadi harusnya tidak ada masalah.
Pilihan lain yakni menggunakan obat yang aman bagi ginjal, karena tidak dimetabolisme di organ tersebut. Obat yang dimaksud yakni elbasvir+grazoprevir, yang sudah mendapat ijin edar dari BPOM pada November 2017 lalu. Konsensus PPHI 2017 mengenai pengobatan hepatitis C, turut mencakup permasalahan ini. Bila sesuai rencana, konsensus ini selesai pada September lalu, dan bisa segera dipublikasi. (nid)