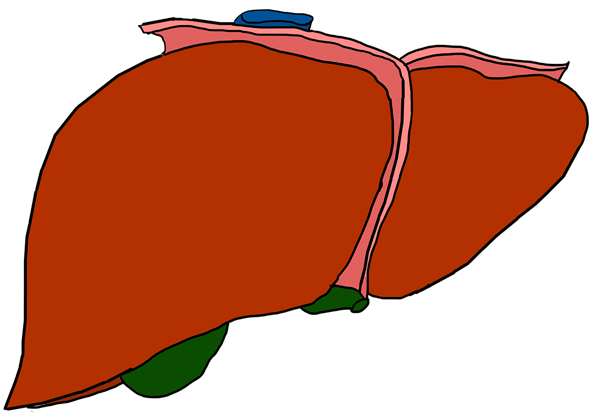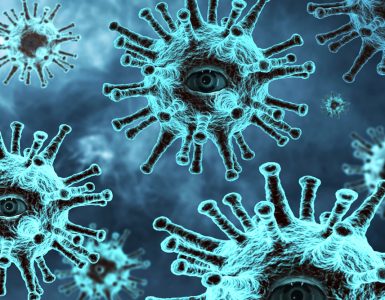Sekitar 90% orang yang terinfeksi hepatitis C berkembang menjadi penyakit kronis. Layanan hepatitis C akan didorong ke layanan BPJS.
Di Indonesia, penyakit lever menduduki peringkat 7 untuk penyakit yang paling banyak menyebabkan kematian (Balitbangkes Kementrian Kesehatan RI 2015). Yang mengkhawatirkan, 95% penderita hepatitis kronis tidak menyadari bahwa dirinya mengidap penyakit ini. Padahal diperkirakan 1 dari 10 orang Indonesia mengidap hepatitis.
Infeksi hepatitis kronik oleh virus hepatitis B (HBV) dan C (HCV) menyumbang proporsi yang besar, untuk penyakit lever di Indonesia. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013, prevalensi hepatitis B mencapai 7,2% (+18 juta orang) dan hepatitis C 1% (+2,5 juta orang).
Bila dibandingkan dengan hepatitis B, infeksi oleh HCV memang tampak kecil. Namun bukan berarti boleh disepelekan. Kronisitas HCV jauh lebih tinggi ketimbang HBV. “Kalau orang dewasa kena hepatitis B, sebanyak 85 – 90% baik sendiri tanpa minum obat apapun. Hepatitis C kebalikannya; 90% tidak sembuh-sembuh,” ungkap dr. Irsan Hasan Sp.PD-KGEH.
Pasalnya, HCV mudah sekali bermutasi sehingga sulit dikenali oleh sistem imun. Akibatnya, HCV sulit dieliminasi dari tubuh. Ini juga salah satu alasan, mengapa vaksin hepatitis C sulit dibuat. Bahkan, antibodi yang terbentuk dari infeksi tidak bisa memberi perlindungan kekebalan tubuh. “Sedangkan hepatitis B, mudah sekali didorong keluar bila sistem imun bagus,” lanjut Ketua Peneliti Hati Indonesia (PPHI) ini.
Sebanyak 80% hepatitis kronis tidak menimbulkan gejala. Gejala baru muncul manakala sudah terjadi sirosis tahap akhir. Tentu kita ingat almarhum politisi Sutan Bhatoegana, yang mendadak masuk rumah sakit dan tidak lama kemudian meninggal dunia akibat kanker lever.
HCV bisa menyebabkan infeksi akut, tapi sangat jarang terjadi. Sepanjang pengalaman dr. Irsan, ia baru menemukan tiga kasus hepatitis C akut. Salah satunya pada perawat yang tertusuk jarum di RS. Setelah dites dan dipantau, dia positif terinfeksi hepatitis C. Infeksi disebut akut bila berlangsung <6 bulan.
Dari infeksi akut, hepatitis C bisa berkembang menjadi kronik, lalu menjadi sirosis. “Lever yang tadinya mulus jadi terbentuk noduler. Itulah sirosis,” terang dr. Irsan. Infeksi akut dan hepatitis kronis masih bisa baik kembali (reversible), tapi bila sudah sirosis maka tidak bisa kembali lagi seperti semula. Perlu sekitar 20 tahun hingga sirosis terjadi, di mana lever mengerut, mengeras dan berbenjol-benjol, karena terbentuk jaringan parut.
Di dalam lever tidak terdapat saraf dan fungsi lever masih bisa bertahan hingga tersisa <30%, sehingga tidak muncul gejala meski sudah sirosis. Orang dengan fungsi lever 50% masih baik-baik saja. Gejala baru muncul bila fungsi lever sudah turun hingga <30%. Gejalanya antara lain jaundice, urin berwarna gelap, kulit terasa gatal, kaki bengkak, dan perut membuncit karena asites.
Hepatitis C utamanya menular melalui darah. HCV juga terkandung di dalam ludah dan cairan sperma, tapi jumlahnya rendah. Kontak dengan liur penderita hepatitis C sulit menyebabkan penularan, kecuali bila liur tersebut mengenai luka terbuka. Anggapan keliru di masyarakat bahwa peralatan makan pasien hepatitis C harus dipisah, perlu diluruskan.
Penyakit ini juga jarang menular melalui hubungan seksual. Penularan secara vertikal dari ibu ke bayi pun sangat rendah, tidak seperti hepatitis B.
Hepatitis C di Indonesia
Di Indonesia, hepatitis C paling banyak ditemukan pada kelompok umur 50-59 tahun. “Namun sekarang ada kecenderungan di usia produktif, 30-39 tahun dan 40-49 tahun. Kita bayangkan dia baru lulus kuliah lalu kena hepatitis C, produktivitasnya bisa terganggu,” ujar dr. Wiendra Woworuntu, M.Kes, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Ditjen P2PL Kemenkes RI.
Dari 6 genotipe HCV, 4 di antara-nya ada di Indonesia (genotipe 1, 2, 3 dan 4). Yang paling banyak adalah genotipe 1, sebanyak 68% (Journal of Viral Hepatitis, 2015). Sayangnya, genotipe inilah yang paling sulit diobati dengan pengobatan yang lama.
Adapun untuk proporsi penderita, berdasarkan data dari Hasil Surveilans Ditjen P2PL 2007-2012, paling banyak yakni pengguna narkoba suntik (penasun). “Ini data dari tahun 2011. Kalau data terakhir, penasun mulai menurun,” ungkap dr. Wiendra. Turunnya angka penasun juga menurunkan kemungkinan pasien HIV yang terinfeksi hepatitis C. “Yang jadi masalah adalah hemodialisis; angkanya mencapai 15,16%,” imbuhnya.
Kemenkes menargetkan eliminasi hepatitis C pada tahun 2030. “Layanan hepatitis C akan didorong ke layanan BPJS, termasuk diagnostik dan evaluasi terapi. Bila diskrining, akan banyak ditemukan penderita,” tutur dr. Wiendra. Ada pertimbangan agar obat untuk hepatitis C tidak hanya bisa diberikan oleh sub spesialis KGEH, melainkan juga oleh spesialis penyakit dalam bahkan dokter umum, “Harusnya juga bisa di Puskesmas. Kalau tidak, eliminasi tidak akan tercapai.”
Skrining dan pemeriksaan
Kemenkes RI berupaya melakukan skrining hepatitis C pada kelompok berisiko. “Misalnya penasun, pasien hemodialisis, keluarga pasien hepatitis C, kontak darah dengan penderita hepatitis C, habis menjalani operasi, dan mereka yang melakukan hubungan seksual tidak aman,” papar dr. Wiendra.
Memang idealnya seluruh anggota keluarga pasien hepatitis C diskrining. Namun, menurut dr. Irsan, perlu dilihat lagi efisiensinya. Berdasarkan data, anggota keluarga dari pasien hepatitis C yang juga menderita penyakit ini angkanya sebesar 13,83%. Ini jauh lebih kecil dibandingkan anggota keluarga dari pasien hepatitis B, yang mencapai 40%.
Skrining untuk hepatitis C dilakukan dengan pemeriksaan anti HCV dalam darah. “Kalau positif, berarti dia sakit,” ujar dr. Irsan. Untuk membuktikan bahwa seseorang benar-benar sakit, dilakukan pemeriksaan lanjutan dengan HCV RNA. Pemeriksaan ini bertujuan melihat ada/tidaknya virus di dalam darah.
Ada dua macam HCV RNA, kualitatif dan kuantitatif. Tes HCV RNA kualitatif lebih akurat ketimbang yang kuantitatif, karena tes kualitatif bisa mendeteksi virus dalam kadar yang sangat rendah sekalipun. Pada tes ini, dilakukan proses PCR (polymerase chain reaction) atau TMA (transcription-mediated amplification) untuk menghitung jumlah virus di darah. Hasilnya dilaporkan “terdeteksi” atau “tidak terdeteksi”. Hasil yang positif (terdeteksi) menunjukkan bahwa tubuh tidak berhasil melawan virus, dan infeksi telah berkembang menjadi kronik. Hasil tes yang menjadi negatif setelah pasien menjalani pengobatan, berarti pengobatan berhasil dan virus tidak lagi terdeteksi dalam darah.
Tes kuantitatif disebut juga viral load; tes ini menunjukkan jumlah pasti virus dalam darah. Hasilnya bisa disebut viral load tinggi (>800.000 IU/L), atau rendah (<800.000 IU/L).
Hasil viral load <615 IU/L menunjukkan kadar virus terlalu rendah sehingga tidak bisa terdeteksi dengan tes ini. Maka perlu dikonfirmasi dengan tes kualitatif. Bila hasil tes kualitatif positif, berarti ada virus di dalam darah tapi kadarnya sangat rendah. Tes kuantitatif juga bisa digunakan untuk monitoring selama pengobatan, untuk menilai keberhasilan terapi.
Nilai viral load tidak menunjukkan derajat kerusakan lever. Untuk menilai derajat keparahan sirosis, bisa dilakukan USG atau biopsi.
“Untuk monitoring hepatitis C, kita sudah punya alat tes cepat molekuler (TCM), dengan mesin yang bisa memeriksa tiga penyakit sekaligus sehingga lebih efisien,” ujar dr. Wiendra. TCM lebih mudah dilakukan dan hasilnya lebih cepat didapat. Pemeriksaan ini terintegrasi dengan program P2 TBC, untuk mendeteksi TB-MDR (tuberculosis yang sudah resisten/kebal dengan berbagai antibiotik) dan HIV. Pemeriksaan ini sudah tersedia di semua layanan.
Komplikasi
Sirosis yang telah terbentuk bisa berkembang menjadi kanker. Bisa pula hepatitis C langsung menyebabkan kanker, tanpa melalui sirosis. Berdasarkan Globocan 2012, kanker lever menduduki peringkat 5 kanker terbanyak di Indonesia dengan insiden 18.121 kasus, dan angka kematiannya sangat tinggi (17.175). Harapan hidup pasien kanker lever sangat rendah. “Pada rerata pasien kanker hati yang datang ke RSCM, diramalkan 4,5 bulan kemudian meninggal dunia,” sesal dr. Irsan. Tidak banyak berubah sejak 15 tahun lalu, meski dengan kemajuan pengobatan di bidang kanker.
Selain sirosis dan kanker, hepatitis C bisa menyebabkan komplikasi ekstra hepatik atau terjadi di luar lever. Misalnya pada ginjal, persendian dan pembuluh darah. Akibat hepatitis C, bisa timbul keluhan seperti rematik. Dari penelitian, orang dengan hepatitis C lebih banyak yang kena kanker limfoma dibandingkan yang tidak hepatitis C. Bukan virusnya langsung yang menyebabkan berbagai keluhan ini, melainkan respon imun tubuh. “Sistem imun tubuh mau membunuh si virus, tapi ‘nyasar’ ke mana-mana dan bikin rusak di tempat lain,” jelas dr. Irsan.
Diskriminasi
Pasien hepatitis C banyak yang menghadapi beban lain: diskriminasi sosial. Di lingkungan kerja, misalnya, cukup banyak yang tidak diterima bekerja, tidak bisa naik pangkat, atau tidak diterima menjadi pegawai tetap bila hasil skrining hepatitis C (atau B) positif. Belum lagi stigma negatif di masyarakat; penyakit ini masih dianggap sebagai aib atau hal yang menakutkan. “Banyak yang keluarganya merasa takut dikucilkan, karena takut dianggap sebagai sumber penularan penyakit,” tutur Marzuita dari Komunitas Peduli Hepatitis.
Pandangan masyarakat soal ini perlu diperbaiki. “Selama tidak ada peradangan, penderita hepatitis bisa bekerja seperti biasa,” ujar Dr. dr. Kasyunil Kamal, M.S, Sp.OK, dari PERDOKI (Perhimpunan Dokter Spesialis Okupasi). Skrining dan pemeriksaan hepatitis diperlukan, hanya untuk jenis pekerjaan tertentu seperti di bidang medis atau pengolahan makanan. Bila hasilnya positif, bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan fungsi lever bagi orang yang akan bekerja di tempat berat atau berpaparan dengan bahan kimia, karena akan memperberat kerusakan lever. Skrining maupun pemeriksaan fungsi hati tidak diperlukan untuk semua jenis pekerjaan, “Apalagi untuk pekerjaan kantoran, harusnya tidak perlu.”
Untuk hepatitis B, sudah ada Surat Edaran dari Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan ketenagakerjaan No. SE.07/BW/1997. Dianjurkan, perusahaan/instansi tidak melakukan pengujian serum HBsAg sebagai alat seleksi, pada pemeriksaan awal maupun berkala. Pertimbangannya, orang dengan dg HBsAg (+) belum tentu menderita hepatitis, selama fungsi hati normal tidak dapat dianggap menderita hepatitis. Apalagi, prevalensi HBsAg (+) di Indonesia cukup tinggi, yaitu 5 – 15%.
Selain itu, penularan ditempat kerja tidak mudah, karena hanya mungkin melalui darah/transfusi darah/suntikan/trans placental. Hal yang sama seharusnya juga berlaku untuk hepatitis C, yang tidak semudah itu akan menular ke rekan kerja, terutama untuk pekerjaan kantoran. (nid)