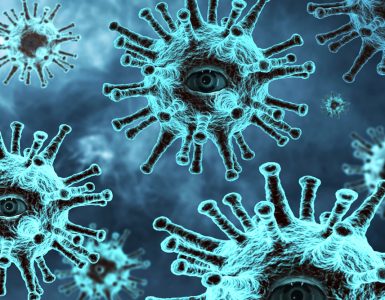Pasien penyakit kronis harus mengontrol penyakitnya, untuk mencegah berbagai komplikasi, termasuk gangguan pendengaran. Fungsi pendengaran harus diperiksa secara rutin.
Berisiko mengalami gangguan pendengaran, pasien kronis perlu melakukan tes fungsi pendengaran secara berkala. “Tes pendengaran dianjurkan setiap tahun, dan ketika pasien merasakan penurunan pendengaran, meski belum saatnya kontrol,” ujar Dr. dr. Siti Faiza Abiratno, Sp.THT-KL, M.Sc dari Kasoem Balance Hearing & Speech Center, Jakarta.
Pemeriksaan meliputi tiga hal berikut ini:
- Tes pendengaran nada murni, untuk menilai suara atau nada dengan volume terendah yang masih bisa didengar oleh pasien. Tes ini mengindikasikan fungsi perifer telinga pasien. Biasanya, tes inilah yang pertama kali dilakukan ketika dicurigai adanya gangguan pendengaran.
Selama tes, pasien duduk dalam booth tertutup, untuk mencegah gangguan suara dari luar. Selanjutnya, pasien diminta memakai headphone atau earphone, dan diinstruksikan untuk menekan tombol atau mengangkat tangannya saat mendengar bunyi pada headphone/earphone. Tes dilakukan pada masing-masing telinga, untuk menilai fungsi tiap telinga dengan akurat.
- Tes audiometri tutur. “Tes ini menggunakan materi tes berupa kata-kata, lalu dinilai berapa persen pasien mampu mengulang kata-kata yang didengar dengan benar,” terang Dr. dr. Siti. Tes ini untuk menilai kemampuan pasien dalam mengenali fonem; menguji fungsi perifer maupun sistem sentral pasien.
- Tes audiometri tutur disertai suara latar (speech in noise test). Materi tes berupa kalimat yang disertai suara-suara lain di sekitar (background noise). Secara umum, gangguan pendengaran bisa dibagi menjadi dua: berkurangnya audibilitas dan berkurangnya kejernihan suara (clarity).
Berkurangnya audibilitas atau volume suara bisa disebabkan kerusakan sel-sel stereosilia bagian luar, sedangkan berkurangnya kejernihan suara berhubungan dengan rusaknya sterosilia bagian dalam atau sistem saraf auditori pusat. Berkurangnya kejernihan suara merupakan gangguan distorsi, dan tidak membaik dengan penambahan volume suara. Tes audiometri tutur dapat menilai fungsi dan kemampuan pendengaran pasien dengan lingkungan suara yang mirip suasana di dunia nyata, di mana ada latar belakang bunyi.
Dr. dr. Siti menegaskan, pasien penyakit kronis harus menjalani pengobatan penyakitnya sesuai arahan dokter yang merawatnya, untuk meminimalkan risiko atau memperlambat munculnya gangguan pendengaran akibat penyakit yang dideritanya. Selain itu, “Pasien juga perlu menghindari suara-suara keras.”
Perkembangan tatalaksana diabetes
Pasien diabetes harus berupaya menjaga kadar gula darahnya terkontrol, dengan target HbA1c <7%. Kadar gula darah yang terkontrol akan memperlambat munculnya berbagai komplikasi, termasuk gangguan pendengaran.
Cukup banyak terobosan baru dalam tatalaksana diabetes, yang menunjukkan hasil menjanjikan. Misalnya saja obat kombinasi metformin dan DPP-4 inhibitor dosis 1x sehari. DPP-4 inhibitor bekerja dengan memperpanjang waktu produksi incretin sehingga mengoptimalkan pelepasan insulin, dengan risiko hipoglikemi rendah. Kombinasi DPP-4 inhibitor dengan metformin yang membuat sel tubuh lebih responsif terhadap insulin, bekerja dengan sinergis dan saling melengkapi. Dosis sekali sehari ditengarai bisa meningkatkan kepatuhan (compliance) pasien minum obat.
Injeksi GLP-1 agonis yang merupakan terapi mimetik, juga termasuk salah satu terobosan dalam tatalaksana diabetes. GLP-1 agonis meningkatkan sekresi insulin dari sel beta pankreas sekaligus menekan sekresi glukagon dari sel alfa. Golongan obat ini juga memperlambat pengosongan lambung dan menimbulkan rasa kenyang, sehingga pasien diabetes tidak makan berlebihan. Pada 5 Desember 2017, Badan Regulasi Obat dan Makanan AS FDA menyetujui semaglutide, GLP-1 agonis dosis 1x seminggu. Studi oleh O’Neil, dkk (Lancet, 2018) menemukan, semaglutide selama 52 minggu—dikombinasi dengan konseling diet dan aktivitas fisik—menunjukkan efek penurunan berat badan (BB) pasien dan ditoleransi dengan baik, dibandingkan plasebo.
Dr. dr. Aris Wibudi, Sp.PD-KEMD memaparkan manfaat alpha lipoic acid (ALA). “Alpha lipoic acid dimanfaatkan sebagai antioksidan. Ternyata, dia juga mampu memperbaiki metabolisme selular,” ungkapnya.
Studi oleh Agathos, dkk (Journal of International Medical Research, 2018), menyebutkan dalam konklusinya bahwa pemberian suplemen ALA pada pasien diabetes dengan gejala neuropati, berhubungan dengan penurunan gejala neuropati dan kadar trigliserida, serta perbaikan kualitas hidup pasien.
Ia mengingatkan, pengobatan utama diabetes adalah perbaikan gaya hidup. “Pada dasarnya, diabetes itu penyakit perilaku. Jadi, yang bisa memperbaikinya adalah perilaku. Sebaik dan secanggih apapun obatnya, kalau tidak disertai dengan gaya hidup, pasti akan berkembang buruk, cepat atau lambat,” tuturnya.
Sebagai Ketua Perhimpunan Edukator Diabetes Indonesia (PEDI), Dr. dr. Aris selalu berupaya mendorong pasien untuk memberdayakan dirinya sendiri dalam mengelola diabetes. Salah satu yang paling sederhana, mengedukasi pasien untuk memahami makanan apa saja yang membuat gula darahnya meningkat tajam. Sehingga, “Pasien sadar mana makanan yang baik, mana yang kurang baik untuknya.”
Pasien juga harus didorong untuk lebih aktif bergerak, dan berlatih fisik secara rutin dan kontinyu. Adapun pilihan latihannya secara umum disesuaikan dengan kondisi fisik dan kesehatannya, usia, dan diabetesnya sendiri.
Pasien gagal ginjal
Pasien penyakit ginjal kronis tahap akhir (PGTA) mutlak membutuhkan dialisis untuk menggantikan fungsi ginjalnya, bila belum bisa menjalani transplantasi. Sayangnya, dialisis juga berdampak buruk terhadap pendengaran, seperti halnya penyakit ginjal itu sendiri. Peyvandi dan Roozbahany (Indian Journal of Otolaryngology Head Neck Surgery, 2013) menyebutkan, dialisis dalam jangka panjang menghasilkan akumulasi materi amiloid di banyak jaringan tubuh; termasuk telinga bagian dalam. Toksisitas alumunium pada pasien dialisis kronis, turut berperan dalam munculnya gangguan pendengaran.
Di Indonesia, terapi pengganti ginjal masih didominasi (95%) oleh hemodialisis (HD); hanya sekitar 3% pasien yang menjalani CAPD (Continous Ambulatory Peritoneal Dyalisis). Kedua pilihan dialisis ini memiliki dampak negatif pada pendengaran, tapi risiko gangguan dengar lebih besar pada pasien HD.
Seperti terungkap dalam studi oleh Vural Fidan, dkk (Acta Acusta united with Acustica, 2012). Studi tersebut menganalisis 79 pasien PGTA yang menjalani HD dialysis, dengan 40 orang sehat. Mereka dibagi menjadi tiga kelompok; kelompok 1 yakni pasien CAPD, kelompok 2 pasien HD, dan kelompok 3 sebagai kontrol. Ditemukan, gangguan pendengaran sensorineureal paling banyak terjadi di kelompok 2, dengan rincian: 9 pasien di kelompok 1 (21,9%); 16 pasien di kelompok 2 (42,1%); dan 1 orang di kelompok 3 (2,5%). Kadar serum urea dan kreatinin pun lebih tinggi di kelompok 2.
Melihat hal ini, makin besar alasan untuk mendukung target Kementrian Kesehatan RI menurunkan HD menjadi 50% dan meningkatkan CAPD jadi 30%. Secara umum, CAPD jauh lebih cost effective dibandingkan HD, dan kualitas hidup pasien pun jauh lebih baik.
CAPD lebih efektif jika dimulai sejak awal. Pasien tidak perlu menjalani HD selama bertahun-tahun baru beralih ke CAPD. HD bisa dilakukan dulu beberapa kali ketika PGTA baru ditemukan, hingga kondisi pasien stabil. Setelah kateter Tenckhoff berhasil dipasang di rongga perut, pasien bisa segera menjalani CAPD.
Pelayanan CAPD sudah tersedia di hampir seluruh daerah di Indonesia, dan sudah terintegrasi dengan HD. Artinya, pusat kesehatan yang melayani HD umumnya juga bisa melayani CAPD.
Pelaksanaan CAPD bukannya tanpa kendala. Cukup banyak peserta CAPD yang akhirnya drop out karena ketersediaan cairan dialisis yang di beberapa daerah (seperti Maluku dan Papua) kadang sulit didapat, akibat distribusi yang terhambat.
Pasien juga harus diedukasi dengan baik untuk selalu menjaga kebersihan kateter serta mengganti cairan CAPD dengan baik, untuk menghindari risiko infeksi. Infeksi juga termasuk faktor yang meningkatkan angka drop out. Umumnya, CAPD hanya berjalan baik selama 2-3 tahun prtama; setelah itu menurun, diduga akibat infeksi.
Peran dokter adalah vital dalam meningkatkan cakupan CAPD, karena keputusan pasien sangat terpengaruh oleh saran dokter untuk terapi pengganti ginjal. Bagi penyedia layanan dialisis, CAPD mungkin dirasa kurang menguntungkan ketimbang HD, karena tidak ada/minim bayaran bagi dokter dan perawat yang membantu pelayanan CAPD. Dibutuhkan intervensi radikal misalnya menerapkan sistem insentif, dan mengubah sistem pembayaran oleh JKN.
Kembali ke masalah gangguan pendengaran, penting untuk menilai fungsi pendengaran pasien PGTA sedini mungkin, dan memasang alat yang sesuai untuk membantu fungsi pendengaran pasien. Hal ini diharapkan bisa mempertahankan fungsi pendengaran, dan pada akhirnya memperbaiki kualitas hidup pasien. (nid)